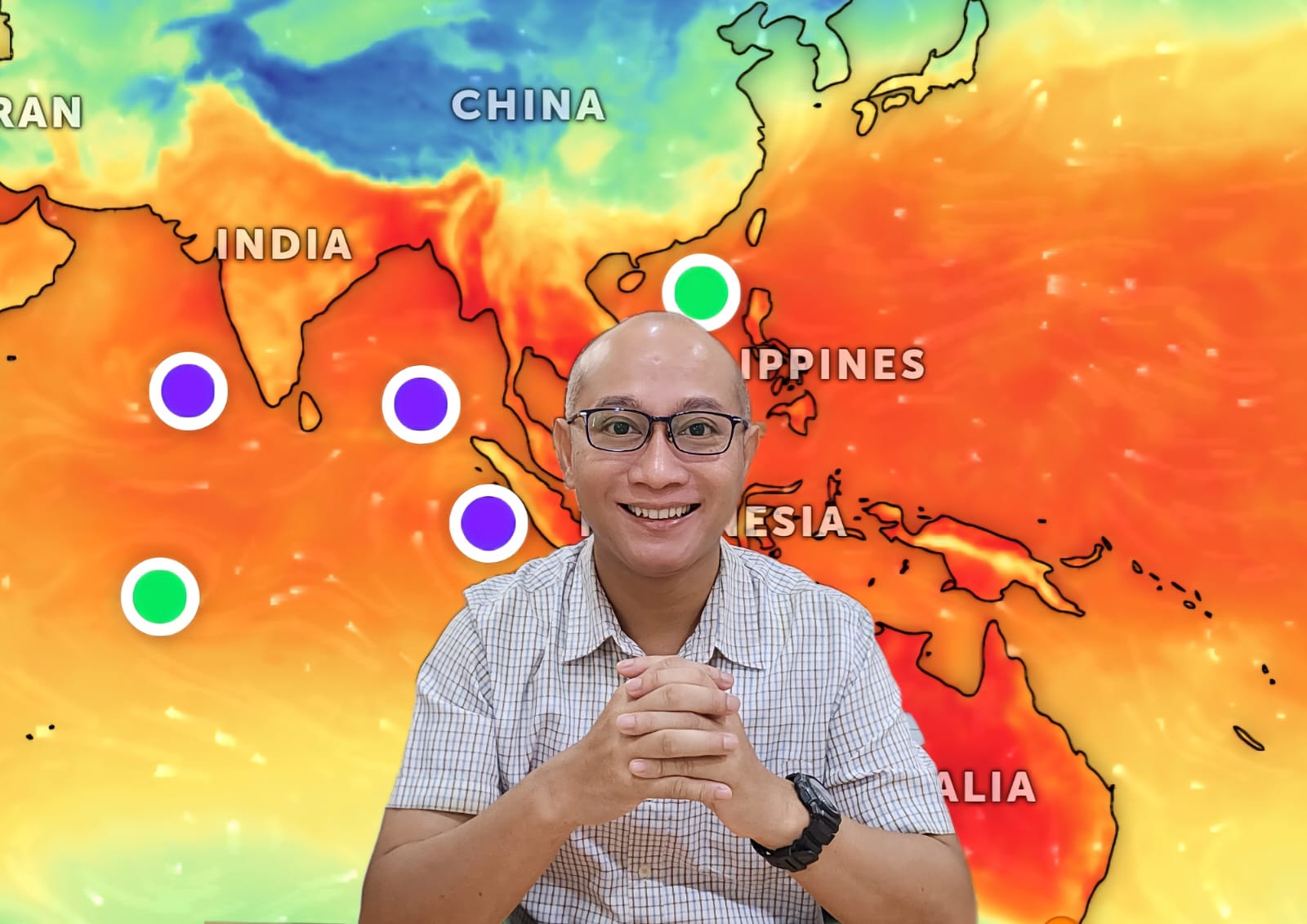Oleh: Michelle Marvella (Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Pelita Harapan)
Pembentukan AICHR sendiri merupakan amanat dari Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN) yang disahkan pada tahun 2008, khususnya merujuk pada Pasal 14 Piagam ASEAN, yang menyatakan bahwa ASEAN akan membentuk badan hak asasi manusia regional sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan HAM di kawasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2009, AICHR resmi didirikan melalui Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (TOR AICHR), yang menjadi landasan operasional, wewenang, serta tanggung jawab lembaga ini.
Sebagai sebuah badan yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN, AICHR berperan sebagai forum strategis bagi negara-negara anggota untuk melakukan dialog konstruktif dan mempererat kerjasama dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Melalui TOR AICHR, lembaga ini diberikan mandat untuk mempromosikan dan melindungi HAM, meningkatkan kesadaran HAM, memberikan konsultasi kepada negara anggota, serta melibatkan dialog dengan pemangku kepentingan yang relevan. Namun demikian, meskipun memiliki kerangka hukum yang jelas, efektivitas AICHR tetap menghadapi tantangan serius dalam praktiknya, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu pelanggaran HAM di negara-negara anggota.
Salah satu permasalahan paling mendasar yang menghambat kinerja optimal AICHR terletak pada lemahnya komitmen politik dari sebagian negara anggota terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana termuat dalam ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012, yang merupakan instrumen deklaratif penting di tingkat regional, ASEAN telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM dengan tetap memperhatikan “konteks nasional dan kekhasan kawasan.” Namun, fleksibilitas prinsip ini justru sering kali dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk menunda atau menafsirkan implementasi HAM sesuai kepentingan domestik mereka.
AICHR juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui berbagai program edukasi dan peningkatan kapasitas. Meskipun demikian, TOR AICHR secara normatif tidak memberikan kewenangan investigatif atau penegakan hukum secara langsung, sehingga dalam banyak hal, AICHR lebih berfungsi sebagai lembaga konsultatif dan edukatif dibandingkan sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat mengikat. Hal inilah yang turut menjadi sumber kritik dari masyarakat sipil terkait keterbatasan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lembaga ini.
Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, seperti tragedi yang menimpa komunitas Rohingya, AICHR kerap dinilai tidak cukup sigap dan tegas dalam memberikan respons terhadap situasi yang memerlukan tindakan segera. Keterbatasan mandat penegakan sebagaimana diatur dalam TOR AICHR membuat lembaga ini sulit untuk bertindak secara proaktif tanpa konsensus negara-negara anggota. Situasi ini menimbulkan keraguan apakah AICHR benar-benar mampu menjalankan amanat Pasal 14 Piagam ASEAN yang menegaskan komitmen perlindungan HAM di kawasan.
Patut disadari bahwa AICHR, dalam menjalankan fungsinya, tidak memiliki kewenangan hukum yang bersifat mengikat, sehingga kemampuan lembaga ini dalam menegakkan hak asasi manusia sangat bergantung pada sejauh mana dukungan politik diberikan oleh negara-negara anggota. ASEAN selama ini memang dikenal menganut prinsip non-interference (tidak saling mencampuri urusan dalam negeri negara anggota), sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2)(e) Piagam ASEAN, yang sering menjadi dalih negara anggota dalam menolak adanya intervensi atau tekanan terkait penegakan HAM domestik.
Selain sebagai pengawas, AICHR juga diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mempererat kerjasama regional di bidang hak asasi manusia. Namun upaya penguatan kerjasama regional ini, meskipun diamanatkan dalam TOR AICHR, kerap terkendala oleh beragamnya sistem hukum, politik, serta budaya hukum negara anggota ASEAN, yang pada akhirnya membuat harmonisasi HAM di kawasan berjalan secara gradual dan sangat hati-hati.
Agar dapat menjalankan perannya secara efektif, AICHR juga perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, dukungan keuangan, serta pengembangan perangkat monitoring yang lebih komprehensif. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip promotion and protection dalam TOR AICHR, yang mewajibkan lembaga ini tidak hanya melakukan promosi tetapi juga memastikan adanya penguatan perlindungan HAM yang substantif.
Partisipasi masyarakat sipil dalam keseluruhan proses kerja AICHR juga memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan adanya akuntabilitas serta representasi suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan TOR AICHR, keterlibatan pemangku kepentingan non-negara diharapkan dapat menjadi sumber masukan konstruktif dalam proses kerja AICHR, namun dalam praktiknya partisipasi tersebut masih sangat terbatas dan terkadang dibatasi oleh faktor politik.
Pada akhirnya, masa depan AICHR sebagai lembaga regional yang menangani hak asasi manusia sangat bergantung pada sejauh mana negara-negara anggota ASEAN bersedia memperlihatkan komitmen politik yang nyata terhadap prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia secara universal.Ketiadaan mekanisme compliance atau sanksi dalam kerangka hukum ASEAN membuat seluruh proses perlindungan HAM sepenuhnya bergantung pada komitmen dan good faith negara-negara anggota. Oleh sebab itu, pembaruan kerangka hukum, penguatan peran masyarakat sipil, serta reformasi kelembagaan menjadi kunci utama untuk menjadikan AICHR lebih efektif dalam menjalankan mandat perlindungan HAM di Asia Tenggara.
* Dosen: Carissa Amanda Siswanto,S.H.,M.H.